Kemarin pagi (5/6) akhirnya buku ini sampai ketangan saya. Di cover depannya tertera nama saya selaku salah seorang penulis. Pak Agus, pegawai pos Mataram mengaku sudah coba mengantarnya kealamat yang tertera dalam paket. Ketika sampai dialamat yang dituju ternyata sepi katanya. Ya, tentu saja sepi karena kami sudah lama pindah kantor kealamat yang baru. Akhirnya sambil berangkat kekantor saya pun mampir kekantor pos Mataram untuk mengambil paket yang dikirim oleh Center for Religious Cross Cultural & Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.
Di buku ini saya menulis sisi baik dari berbagai kebaikan yang ditimbulkan oleh keberagaman agama di Lombok. Saya memang sengaja ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa tanah Lombok bukan bisa menyuguhkan berbagai situs agama yang bisa dilihat tapi juga menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Pada tulisan-tulisan saya sebelumnya saya pernah beberapa kali menulis tentang konflik antar dan intern agama di Lombok. Saya pernah menulis konflik Islam - Hindu, konflik Islam-Kristen, konflik internal Islam dan konflik diinternal agama Budha. Kalau mengigat data dan fakta yang terjadi, seolah konflik agama tidak mau beranjak dari gumi Lombok.
Saat diberikan pekerjaan rumah (PR) setelah mengikuti Sekolah Pengelolaan Keberagaman (SPK) angkatan pertama selama 12 hari di Hotel UGM pada awal 2013 silam. Saya memutuskan untuk menulis hal positif antar hubungan agama di Lombok. Tentu tanpa bermaksud ingin mengabaikan sejarah kelam relasi antar umat beragama di Lombok. Diluar itu ternyata tokoh-tokoh agama terdahulu sudah menanamkan bibit-bibit tolernasi agar buahnya bisa dipetik oleh generasi berikutnya. Tinggal kembali kepada kita, apakah kita bersedia memetik buah-buah toleransi itu atau malah menganggap sebagai ‘buah terlarang’ yang haram untuk diambil intisarinya.
Saya lalu menelusuri jejak-jejak titik temu antara orang Islam dan Hindu di Pura Lingsar, Lombok Barat. Dan ternyata didalamnya ada Kemaliq-situs yang sangat dihormati oleh orang Hindu dan Islam. Menurut pemangku Pura Lingsar ternyata kemaliq itu bukan hanya dihormati tapi juga rutin dikunjungi setiap tahun oleh komunitas Hindu, Islam dan Cina. Lalu kenapa Kemaliq itu sangat dihormati, itulah yang saya ungkap dalam buku ini dengan judul, “Kemaliq Pura Lingsar : Ruang Pertemuan Islam-Hindu di Lombok” (hal-147).
Ketika saya mendatangi Pura Lingsar, saya pun menyaksikan langsung sekelompok orang etnis Cina sedang membuat acara syukuran didalam konflek pura. Itu membuktikan bahwa adanya titik temu antara Hindu, Islam dan Tionghoa di Pura Lingsar bukan hanya sebatas cerita tapi fakta nyata yang bisa kita dilihat. Hal itu semakin jelas dengan diadakannya Festival Perang Topat yang berlangsung meriah setiap tahun dimana pesertanya berasal dari komunitas Islam, Hindu dan Cina.
Setelah bertanya, melakukan wawancara dan mencari berbagai referensi saya baru tahu ternyata pemangku (penjaga) dari Pura Lingsar itu ternyata dua orang. Satu orang berasal dari komunitas Muslim, satunya lagi dari Hindu. Kedua pemangku itu diberikan hak mengelola tanah pecatu untuk digarap. Maka kalau kita melihat wujud bangunan Pura Lingsar dari dekat apa lagi dari jauh, kita bisa jadi tidak akan percaya didalam konflek bangunan yang sangat identik dengan Hindu ternyata terdapat Kemaliq sebagai simbol titik temu antara Islam, Hindu dan Cina di Lombok.
Kalau rumah ibadah yang letak bangunannya saling berdekatan – itu banyak terdapat diberbagai tempat. Tapi satu konflek bangunan yang didominasi oleh agama tertentu ternyata merasa dimiliki oleh komunitas agama yang berbeda, hal ini tentu sangat luar biasa. Kejadian seperti ini tentu akan mungkin terjadi manakala telah terbangun hubungan yang erat sebelumnya sehingga masing-masing pihak tetap saling menghormati. Termasuk adanya rasa kepemilikan bersama terhadap satu bangunan tertentu oleh masing-masing umat beragama yang berbeda.
Saya yakin cerita Kemaliq yang ungkapkan dalam buku ini bukan satu-satunya peninggalan sejarah yang menunjukkan ‘mesranya’ hubungan antar penganut agama di Lombok. Kalau kita tekun dan konsen menelusuri jejak-jejaknya, saya percaya kita akan menemukan praktek-praktek baik lain ditengah masyarakat akan tersemainya kehidupan yang saling menghargai ditengah masyarakat tanpa sekat-sekat pembatas antar agama, etnis atau suku. Bagi saya, perbedaan itu malah menjadi perekat bagi kita untuk saling mengenal dan mempelajari prinsip hidup masing-masing. Maka alangkah indah hidup ini bilamana masing-masing pihak tidak mendegasi pihak lain.
Buku “Praktek Pengelolaan Keragaman di Indonesia-Kontestasi dan Koeksistensi” menuturkan kepada pembaca bahwa ada peristiwa tidak baik sekaligus praktek-praktek baik dalam hubungan antar agama di tanah air. Dan buku ini kembali merangkum pahit-manisnya hubungan antar agama dan masyarakat di Indonesia. Apa lagi para penulisnya berasal dari Aceh, Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, NTB dan NTT.
Terakhir, kehadiran buku ini akan selalu mengingatkan saya akan pengalaman mencicipi ‘sekolah pasca sarjana’ di UGM, berkunjung kepesantren waria, kelompok penganut kepercayaan dan terakhir dijamu makan malam oleh Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X didalam konflek Kraton Jogjakarta. []
Mataram, (8/6) 2015
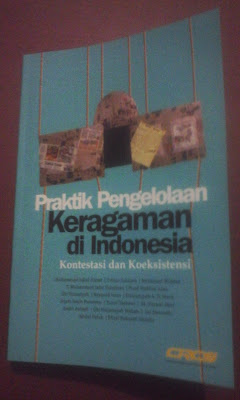
Komentar
Posting Komentar